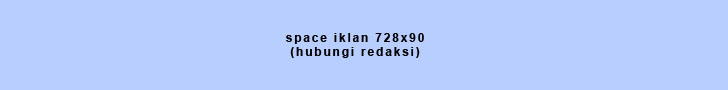|
| Muhamad Arsat (Photo: Istrimewa) |
Program industri kelapa di Kabupaten Kepulauan Selayar, melalui gerakan penanaman besar-besaran Gerakan Menanam Lima Juta Pohon Kelapa (Gemerlap), dapat dimaknai sebagai bentuk intervensi pembangunan yang menarik jika dilihat melalui perspektif antropologi ekonomi. Karl Polanyi dalam karyanya The Great Transformation (1944) menyatakan bahwa industri adalah jawaban dari banyak persoalan sosial. Industri memungkinkan orang bekerja, bertukar, dan memproduksi bukan hanya demi keuntungan, tetapi juga demi kewajiban sosial, menjaga keharmonisan, serta memperkuat ikatan kekerabatan. Dengan demikian, industri tidak semata dipahami sebagai aktivitas produksi dan distribusi barang, melainkan juga sebagai praktik yang melekat pada struktur sosial, nilai budaya, dan dinamika masyarakat lokal.
Gerakan penanaman lima juta pohon kelapa ini jelas merupakan proyek prestisius yang secara simbolik maupun praktis menempatkan kelapa sebagai komoditas sentral dalam narasi pembangunan daerah. Namun, dari sudut pandang antropologi ekonomi, program ini tidak bisa dilepaskan dari pemahaman lokal tentang tanah, tenaga kerja pemuda, serta relasi sosial yang tercipta di sekitarnya.
Di sisi lain, pembangunan industri hilirisasi kelapa—seperti minyak kelapa, kopra, Virgin Coconut Oil (VCO), nata de coco, santan, minuman isotonik dari air kelapa, briket, olahan sabut kelapa, hingga gula kelapa—secara teoritis menjanjikan nilai tambah ekonomi. Namun, tafsir antropologi ekonomi mengajak kita melihat lebih dalam: bagaimana nilai itu diciptakan, didistribusikan, dan siapa yang paling diuntungkan? Industrialisasi komoditas kelapa semestinya dikelola oleh pemuda terampil dan terlatih. Akan tetapi, logika ekonomi modern yang menekankan efisiensi dan keuntungan finansial sering kali mengabaikan nilai-nilai lokal seperti gotong royong, solidaritas, dan keberlanjutan ekologis. Jika aspek-aspek ini terpinggirkan, industrialisasi justru dapat melemahkan pelaku ekonomi kecil serta merusak tatanan sosial yang menopang kehidupan masyarakat Selayar.
Dalam kerangka antropologi ekonomi, manfaat industri kelapa dan penyerapan tenaga kerja pemuda terampil tidak semata-mata diukur dari angka pertumbuhan atau statistik produksi. Industri kelapa bukan hanya tentang komoditas bernilai jual tinggi, tetapi juga merupakan ruang sosial dan budaya tempat nilai, relasi, dan identitas masyarakat berinteraksi.
Keterlibatan pemuda terampil dalam industri kelapa bukan sekadar soal lapangan pekerjaan. Lebih dari itu, hal ini menunjukkan adanya transformasi nilai ekonomi—bahwa generasi muda tidak hanya berperan sebagai pelaksana, melainkan juga agen perubahan dalam memaknai kerja, tanah, dan hasil alam. Bagi masyarakat Selayar, kelapa bukan sekadar pohon penghasil komoditas, melainkan bagian dari harta, siklus kehidupan, warisan leluhur, dan simbol keberlanjutan. Karena itu, ketika industri kelapa berkembang dan melibatkan pemuda secara aktif, yang terjadi bukan hanya mobilisasi tenaga kerja, melainkan juga regenerasi pengetahuan lokal yang berpadu dengan inovasi modern.
Antropologi ekonomi mengajarkan bahwa ekonomi tidak bisa dipisahkan dari konteks sosialnya. Saat pemuda bekerja di sektor industri—mengolah minyak, menciptakan produk turunan, hingga memasarkan secara digital—mereka sesungguhnya sedang menegosiasikan posisi dalam struktur sosial baru. Mereka tidak hanya “bekerja”, melainkan juga mengaktualisasikan diri dalam sistem yang menyatukan produktivitas, martabat sosial, dan harapan masa depan. Proses ini penting karena melibatkan transfer nilai dari generasi tua ke generasi muda, sekaligus adaptasi nilai global seperti teknologi, kewirausahaan, dan efisiensi, yang dipadukan dengan kearifan lokal.
Dengan demikian, manfaat industri kelapa yang dibangun pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak semata peningkatan pendapatan atau ekspansi pasar, melainkan juga pembentukan makna ekonomi baru di tingkat komunitas. Pemerintah perlu memberi ruang luas bagi pemuda Selayar agar tetap sejahtera tanpa harus meninggalkan Tana Doang. Sebab, di tangan pemuda terampil, industri kelapa bisa menjadi sarana untuk merajut kembali hubungan antara kerja, tanah, dan harapan—bukan dalam kerangka eksploitasi, melainkan dalam semangat keberlanjutan dan penghargaan terhadap nilai lokal. Tafsir antropologi ekonomi mengingatkan bahwa ekonomi yang hidup adalah ekonomi yang terhubung dengan manusia, relasi sosial, sejarah, dan budaya. Dengan begitu, pemuda yang terserap dalam industri kelapa bukan hanya sumber daya, melainkan juga pewaris sekaligus pembaharu sistem ekonomi yang berpijak pada tanahnya sendiri.
Oleh karena itu, program Gemerlap layak disambut baik. Program ini bukan sekadar langkah teknokratis untuk menumbuhkan ekonomi, tetapi juga gerakan sosial yang menghubungkan tanah, manusia, masa depan, dan generasi muda. Jika dijalankan dengan prinsip keadilan sosial, kelapa tidak hanya akan tumbuh sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga menjadi penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus simbol harapan, kemandirian, dan kesejahteraan.
Penulis: Muhamad Arsat, Pemuda dan Aktivis Kabupaten Kepulauan Selayar